Judul : Matinya Demokrasi dan Kuasa Teknologi
Penulis : Jamie Bartlett
Penerjemah : Enda Ara
Penerbit : Global Indo
ISBN : 978-623-96116-2-0
Resentor : Resensi Institut
Demokrasi menghadapi ancaman yang tidak main-main. Setelah beberapa abad demokrasi menjadi pilihan paling logis untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal, yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, akhirnya dapat terjungkal bukan karena ideologi komunis ataupun fasis, melainkan di hadapan ideologi baru yang disebut teknologi digital—sebuah panoptikon baru yang dapat mengendalikan segala aspek dalam kehidupan hingga kehendak bebas manusia—sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Penganut ideologi ini adalah mereka para tecnophilia yang melihat teknologi digital (yang selanjutnya disebut internet) sebagai mukjizat baru yang melahirkan peradaban baru bagi ummat manusia.
Jamie Bartlett jurnalis asal Inggris menunjukkan fenomena itu dalam bukunya yang berjudul Matinya Demokrasi dan Kuasa Teknologi yang diterbitkan Global Indo tahun 2021. Pembahasan mengenai teknologi, khususnya internet menjadi perbincangan seiring perkembangan teknologi digital itu sendiri. Internet telah membawa kita pada babak baru kehidupan manusia, di mana manusia diperhadapkan pada sebuah revolusi digital yang mendisrupsi peran-peran manusia. Internet sebagaimana pisau yang memiliki dua sisi yang sama daya irisnya. Sayangnya, internet selalu muncul dengan sisi positifnya, bahwa ia membawa peradaban baru bagi umat manusia dengan tidak ada lagi sekat ruang dan waktu, informasi lebih mudah didapatkan, artificial intelligence akan mempermudah segala urusan manusia dan kehidupan akan jauh lebih baik dengan kehadiranya. Namun, melupakan sisinya yang lain. Sehingga pada tulisan ini kita akan melihat internet dari sisinya negatifnya. Bagian yang akan membuka mata kita, kalau internet dapat menyingkirkan manusia dan menghancurkan demokrasi.
Internet dengan kuasa datanya dapat memengaruhi kehendak bebas kita. Manusia selalu yang yakin kalau ia adalah spesies penguasa bumi yang berada dalam puncak rantai makanan karena hasil evolusinya memiliki akal untuk berpikir dan kehendak bebas. Namun, bagaimana jika kehendak bebas manusia itu ternyata dapat dikendalikan big data tanpa kita sadari? atau apa yang Yuval Noah Harari sebut dalam Homodeus sebagai “dataisme” bahwa dengan data yang cukup pikiran manusia dapat dipahami dan bahkan dipengaruhi. Manusia menjadi objek dari bagaimana data, AI, dan algoritma akan menunjukkan kuasanya atas manusia. Contoh paling sederhananya: dalam platform media sosial, apa yang kita cari di Facebook akan muncul di Instagram dan begitu juga di platfrom yang lain. Kita terkejut seolah internet lebih mengetahui kita dari diri kita sendiri, sehingga sesuatu yang tadinya bukanlah kita seakan menjadi kita karena AI yang telah bekerja memberi kita preferensi kepada hal-hal tertentu.
Baca juga : Resensi Buku Etnografi Dunia Maya Internet
Di Internet kita memiliki domisili baru. Jamie Bartlett menyebutnya sebagai kampung global. Di dalamnya kita dibagi berdasarkan preferensi kita terhadap sesuatu berdasar pembacaan algoritma Filter bubble di mana kita akan dikelompokkan berdasar riwayat klik (like,comment,share, etc), pencarian, dan ruang gema echo cambers yang menjebak kebenaran yang kita pahami berkutat satu komunitas digital saja sehingga ketika kita menyukai kebenaran tertentu, maka internet akan menampilkan segala bentuk iformasi yang mendukung itu, begitupun sebaliknya. Inilah penyebab Gerakan politik populis meningkat. Di Indonesia misalnya, internet berhasil mebelah kita dalam dua kelompok: cebong dan kampret. Masyarakat awam pun yang antipati terhadap politik bisa menjadi seorang fanatik kepada satu kelompok karena terpapar algoritma internet yang menafsirkan prefensi politik kita dengan menampilkan informasi yang sesuai dengan riwayat klik dan pencarian kita di platform digital. Keadaan itu memicu kekacauan dan kebingungan sementara kedua hal itu menurut Hanna Arendt merupakan sasaran karisma demagog dalam arti kata lain melahirkan benih-benih totalitarisme karena warga yang bingung dan kacau pasti membutuhkan keteraturan dan para pemimpin otoriter menawarkan itu.
Kuasa teknologi tidak hanya sampai di situ, bahkan di Amerika tahun 2016 menjadi bukti paling nyata bagaimana teknologi digital bisa mengubah pemilu dan mengalahkan survei. Trump membuat proyek Alamo di mana di dalamanya terdapat perusahan data Cambridge Analytica sebagai tim pemenangan. Kehadirannya mengubah percaturan suara berbasis data. Strategi politik yang digunakan pun akhirnya lebih efektif dan efisien. Mereka yang belum menentukan pilihannya merupakan sasaran utama dari strategi berbasis data ini. Akhirnya ada dua negara bagian Amerika Serikat yang merupakan basis suara demokrat selama puluhan tahun justru memenangkan Trump dari partai Republik. Betapa suara pemilih bisa dikendalikan bukan lagi dengan cara konvensional money politic melainkan cara yang lebih halus, kendatipun sama-sama membunuh demokrasi.
Baca juga : Rekomendasi Buku Tentang Sejarah Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan
Selain itu, kuasa internet yang lain: menciptakan kecerdasan buatan yang menawarkan fungsi yang jauh lebih baik dari manusia: dari mobil swakendali yang lebih memiliki akurasi kecelakaan yang rendah, aplikasi analisis kesehatan yang akan memberi rekomendasi kesehatan dengan risiko kegagalan yang jauh lebih kecil, dan lainya, membuat manusia mulai khawatir. Karena persoalan lain akan muncul, yaitu pengangguran. Di saat yang sama ketimpangan akan semakin besar antara para penguasa teknologi digital dengan masyarakat biasa dan ini tidak sehat dan tidak adil. Mereka akan menjadi penguasa dunia dengan mendistorsi politik serta ekonomi dengan kekuasaan data yang dimilikinya. Dari beberapa orang terkaya dunia, setidaknya terdiri dari para pendiri teknologi ditigal pada rangking paling atas.
Sebagaimana dunia nyata, di dunia digital ada juga pahaman yang melawan yang dominan. Dalam hal ini Jamie Bartlett menyebutnya sebagai kripto-anarki sebuah kelompok atau filosofi baru yang muncul untuk tidak memghadirkan negara dalam interaksi digital di mana privasi sebagai hal paling utama. Sayangnya kehadiran filosofi ini justru ikut mengancam demokrasi karena menolak kehadiran negara sementara negara memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan demokrasi yang ideal. Lalu, apakah internet ini memang membunuh demokrasi dan sama sekali tidak dapat memperkuatnya?
Jamie Bartleet membawa kita ke dalam dua pilihan di masa depan mengenai persoalan kuasa internet dan matinya demokrasi untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu utopia di satu sisi dan distopia di sisi yang lain. Yang mana hal ini tergantung dengan pandangan politik kita sendiri. Jika kita seorang yang optimis terhadap internet maka kita masuk dalam kelompok utopia karena internet telah membawa segala hal yang baik sehingga internet bukan masalah bagi demokrasi, tetapi sebaliknya jika kita skeptis terhadap internet maka kita masuk dalam golongan distopia yang mengkhawatirkan masa depan pemerintahannya yang akan kehilangan kendali penuhnya.
Oleh karena itu Jamie Bartleet punya dua puluh cara bagaimana menyelamatkan demokrasi di tengah kuasa teknologi. Di antaranya adalah miliki pendapatan pribadi agar tidak begitu bergantung pada teknologi, lawan distraksi atau gangguan yang ada di internt, tetap berpikir kritis, dan menertibkan algoritma. Dua puluh hal itu juga senada dengan empat rumusan bagaimana kita seharunya di internet oleh program siberkreasi kominfo dengan empat hal, di mana kita harus punya etika digital, kecapakan digital, membangun budaya digital yang bijak, dan memahami keamaan digital.



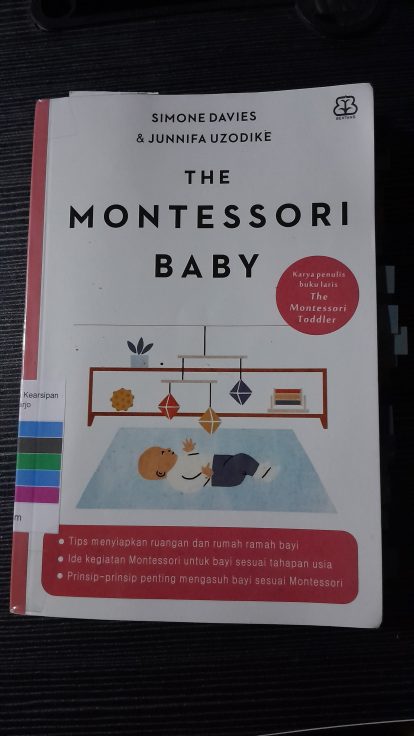

 Resensi Buku Dari Filsafat Ke Filsafat Teknologi – Yesaya Sandang
Resensi Buku Dari Filsafat Ke Filsafat Teknologi – Yesaya Sandang
2 Replies to “Resensi Buku Matinya Demokrasi dan Kuasa Teknologi – Jamie Bartlett”